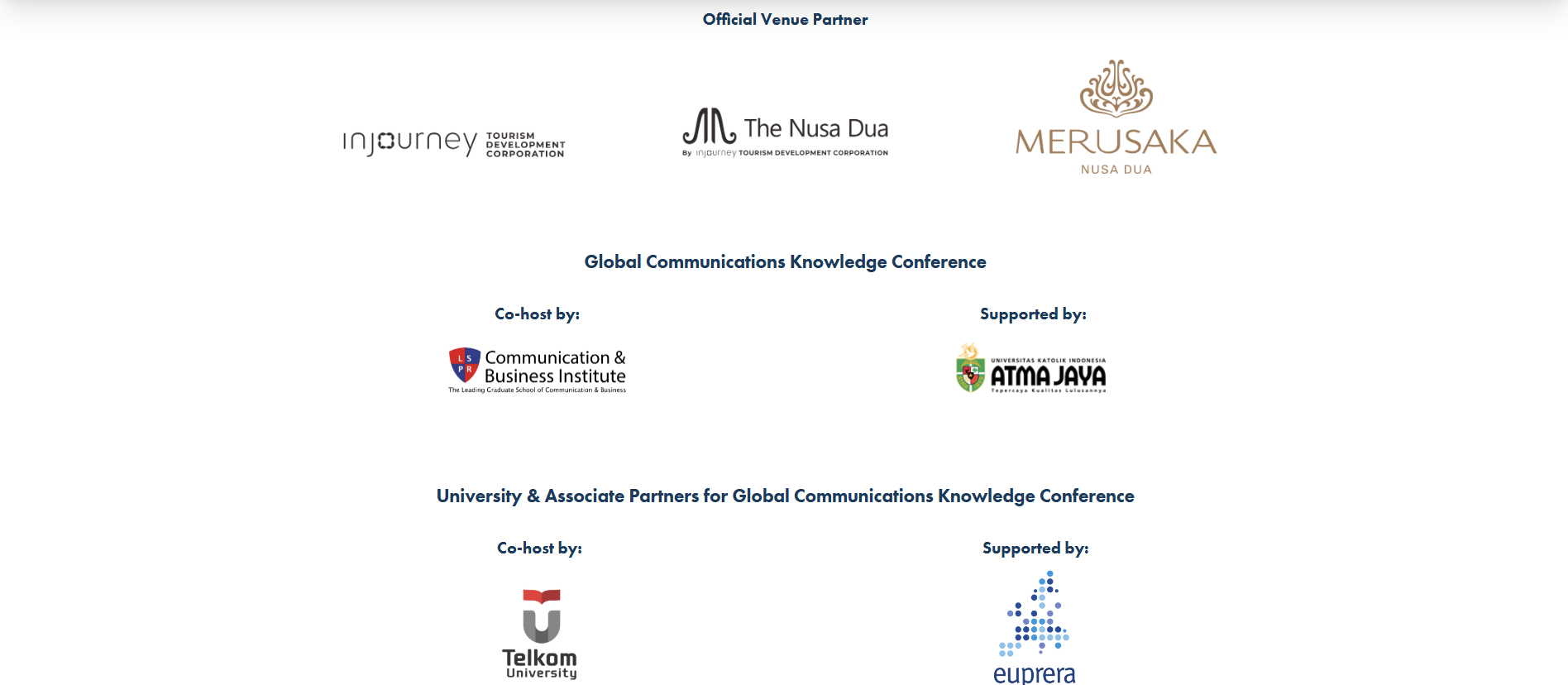Bandung, 3 Juni 2021 – Sematan koran, tv, radio sebagai legacy media kian usang dan berkurang audiensnya sudah kerap kita dengar, seraya kita semua asyik masyuk mengakses new media yang berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK), personal, serta canggih nan memuaskan.
Faktanya, hikmah di balik musibah pandemi justru diraih media legacy! Survei Nielsen di 11 kota besar Indonesia per 22 April 2021 mencatat pembaca media cetak per kuartal empat 2020 sebanyak 2,6 juta atau naik dari kuartal empat 2019 sebesar 2,1 juta.
Bahkan tercatat nilai belanja iklan 2020 mencapai Rp229 triliun atau naik 26% dibandingkan pendapatan 2019 Rp182 triliun. Apakah media baru jawaranya? Ternyata tidak, karena tetap masih televisi dengan proporsi pendapatan 70%.
Ketika Youtube disebut-sebut jauh mengalahkan popularitas televisi, faktanya televisi masih jadi ruang dominan pariwara. Radio pun disebut Nielsen berpendapatan stabil, manakala orang menilai hanya didengarkan di mobil saja.
Media cetak lebih menarik lagi. Betul penetrasi pembacanya terus turun namun tidak otomatis porsi iklan tandas sudah. Terlebih, nyaris semua media cetak mendigitalisasi kontennya, yang mana pendapatan media digital 2020 naik empat kali lipat!
Padahal sebelumnya, riset penulis merujuk data Dewan Pers, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan PwC Perspective from Global Entertaiment and Media Outlook berkebalikan itu semua. Laju pertumbuhan koran di dunia tercatat minus 8,3% sementara Indonesia rerata tutup 80 penerbitan koran selama 2013-2017.
Di sisi lain, kenaikan pertumbuhan eksponensial netizen 200% per tahun dengan motivasi terbesar penggunaan internet adalah media sosial dan hiburan, baru membaca berita di urutan ketiga. Dengan asumsi pertumbuhan minus penerbit media massa cetak terus terjadi, motivasi penggunaan new media masih di media sosial dan hiburan (bukan berita), serta melihat jumlah sisa penerbit koran eksisting, maka usia koran di Indonesia tersisa 10,6 tahun.
Lantas, apa penyebab sejumlah indikator biru –yang cukup mengejutkan– dari media konvensional di atas? Nielsen mencatat, apabila hanya merujuk data 2019-2020, yang utama adalah pandemi membuat waktu dan atensi masyarakat mengakses informasi meningkat khususnya informasi kesehatan. Selain itu, kebijakan work/school form home setahun lebih ini, juga otomatis membuat aktivitas mengakses legacy media menjadi pilihan kembali. Mungkin, ini salah satu barokah di balik musibah manakala media massa saat normal sebelum pandemi pun bingung bagaimana lagi caranya menaikkan pembacanya.
Melihat situasi-situasi tersebut, maka ada strategi dari insan hubungan masyarakat yang kiranya perlu dikalibrasi.
Pertama, tinjau ulang atas strategi eksisting kehumasan yang sekiranya lebih memprioritaskan new media dibandingkan legacy media.
Pada beberapa tahun terakhir, penulis menemukan strategi perusahaan dan humas yang dengan ekstrem tidak lagi menjadikan media massa sebagai mitra publikasinya. Alih-alih mengundang wartawan untuk press conference atau kirim press release misalnya, humas hanya mengundang selebgram, youtuber, blogger, bahkan buzzer dalam aktivitas komunikasi publiknya.
Sekalipun muncul komplain dari jurnalis, humas bergeming karena punya anggapan lemah nirdata jika legacy media sudah tidak ditonton. Hal ini semata karena dirinya pengguna aktif new media, tanpa mau mempelajari data faktual secara paralel, sehingga vonis pemilihan khalayak media dijatuhkan serampangan. Sepatutnya seimbangkan saja keduanya karena menafikan salah satunya adalah kebijakan tidak tepat pada era konvergensi media baru dan media lama ini.
Jika pendekatan yang disasar adalah upaya branding kepada segmen khalayak terbatas namun memiliki status sosial yang kuat, maka legacy media layak jadi pilihan. Bangunlah relasi dengan wartawan koran/tv/radio, termasuk beriklan yang sifatnya mengokohkan eksistensi.
Akan tetapi, jika yang dikejar adalah imaging atau popularisasi entitas yang nantinya berujung pada keterpilihan jenama dari merek-merek lainnya, maka new media layak jadi opsi utama. Luruhkanlah pola pikir dikotomis dalam relasi media ini karena khalayak itu terentang demikian luas serta tak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal.
Kedua, humas harus aktif namun selektif memproduksi konten. Ketika pandemi mencuatkan isu kesehatan, maka sekalipun sehari-hari humas manufaktur misalnya, namun selalu bisa kaitkan entitasnya dengan isu pandemi. Pilih dan relevansikan konten yang diproduksi dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya terkait Corona, yang terbukti menaikkan peningkatan jumlah pembaca koran tadi.
Pun demikian saat menyapa populasi pembaca lebih luas yakni warganet, corak warna konten pun dibuat beririsan. Konten selalu nyambung hanya dibedakan dari sisi kemasan merujuk karakter audiens berbeda. Keteraksesan yang sama tumbuh dari kedua media jelas mempersyaratkan kerja keras humas agar lebih mengustomisasi konten sebagai sebuah keniscayaan di era sekarang.
Ketiga, humas bermitra dengan media konvensional tak sekedar kirim rilis dan beriklan. Momentum saat ini memungkinkan relasi dijalin dengan pendekatan solusi bersama masalah riil masyarakat. Misal momen Ied Fitri mendatang, temuan masalah jurnalis di lapangan terkait warga miskin minim perhatian, bisa disinergikan mandatori perusahaan untuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Maka, selain jurnalisme solusi hadir, juga citra positif perusahaan terjaga/terkerek.
OPINI oleh Muhammad Sufyan Abdurrahman, Dosen Digital PR Fakultas Komunikasi Bisnis Telkom University